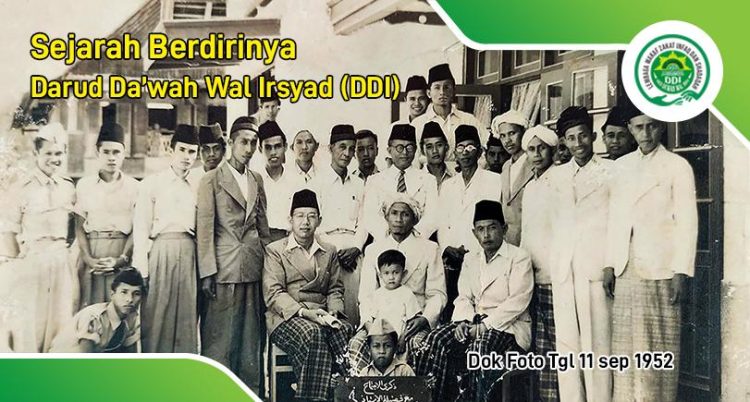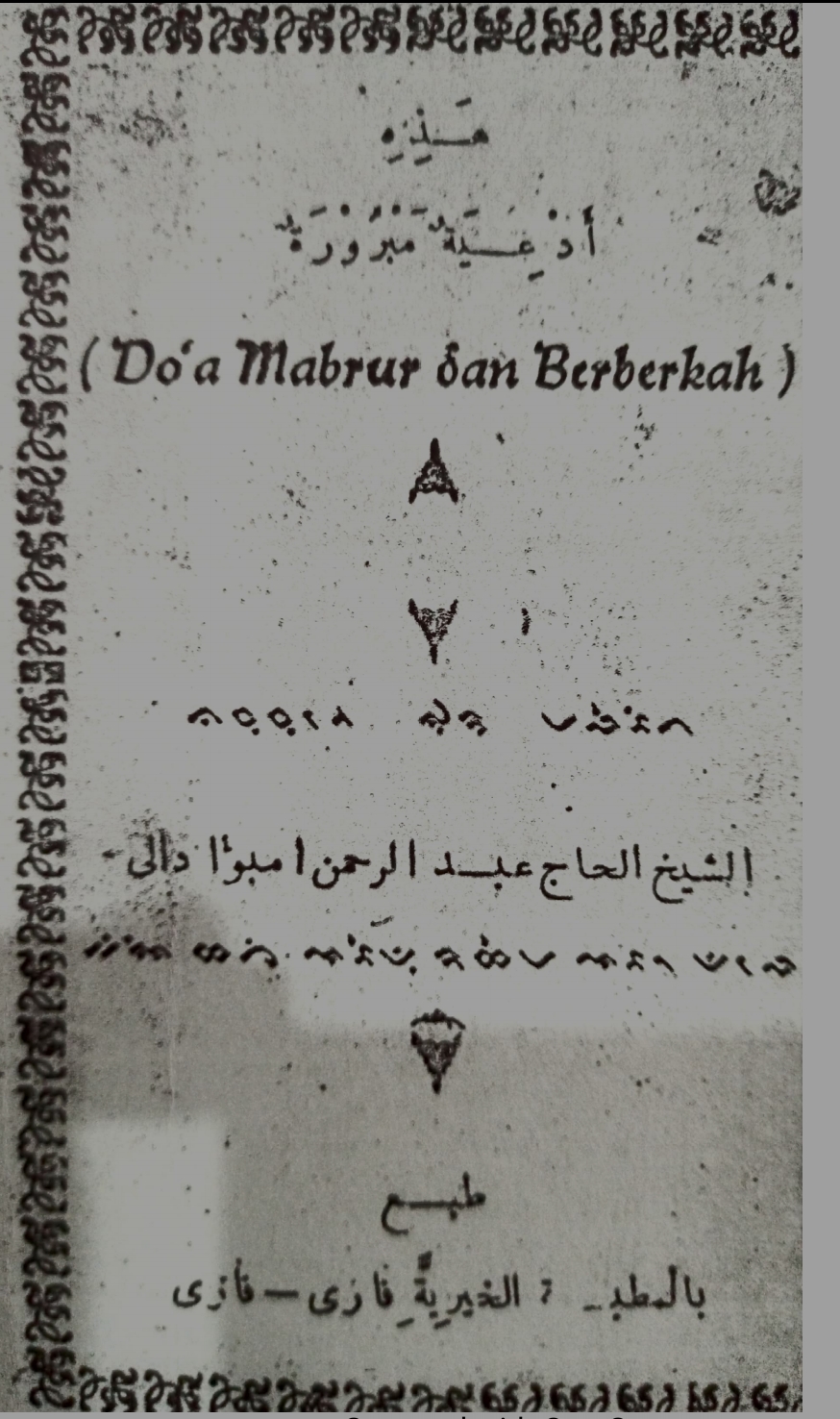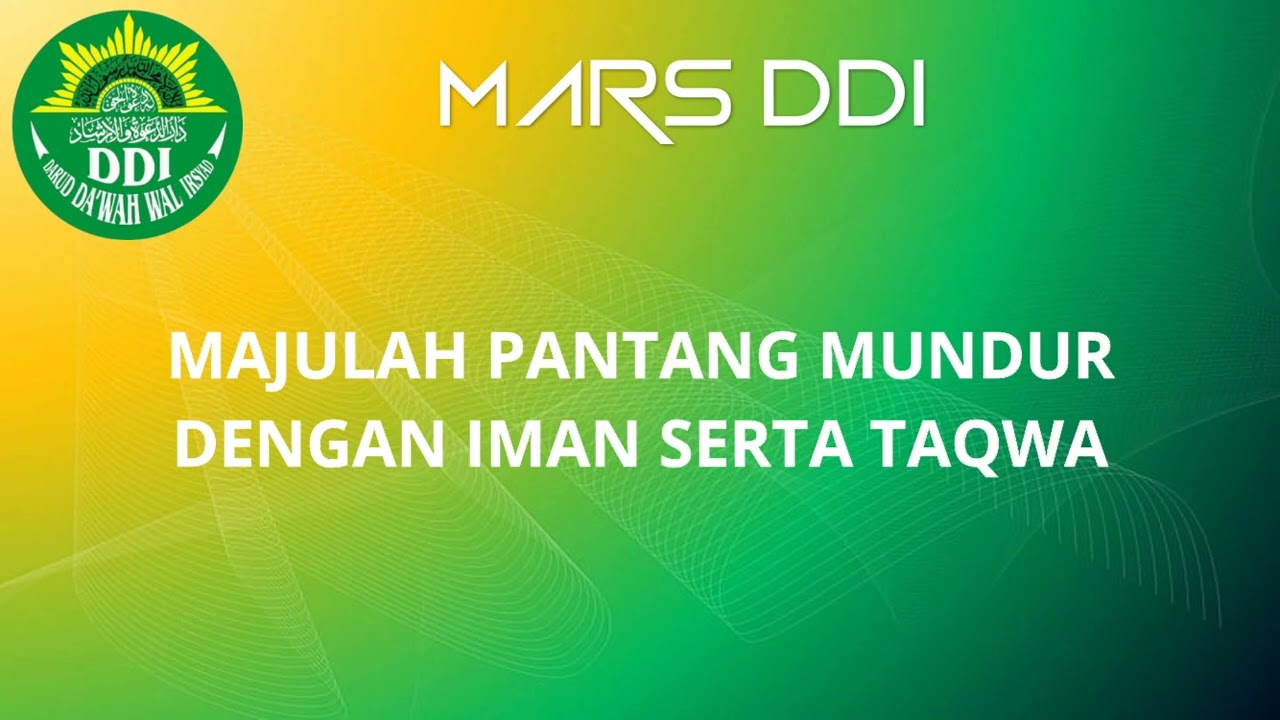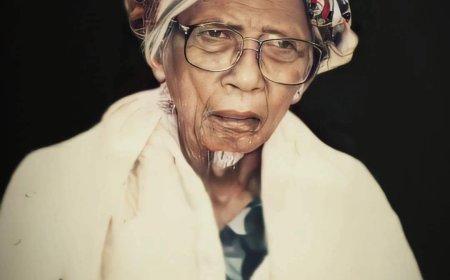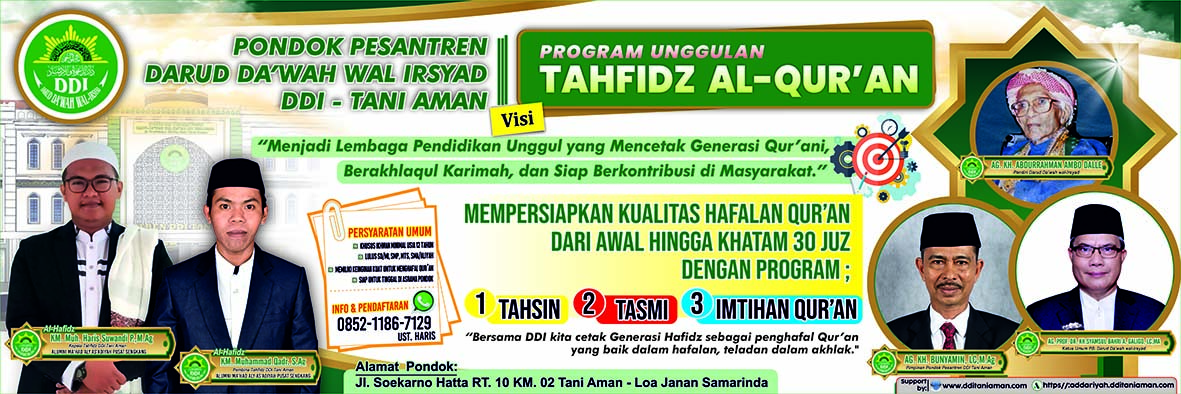Inklusivitas Pendidikan Agama sebagai Pilar Etis Masyarakat Majemuk

Pendidikan agama memiliki fungsi transformatif dalam membentuk karakter peserta didik. Fungsi ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Dalam konteks masyarakat majemuk, pendidikan agama semestinya berkarakter inklusif. Inklusivitas menjadi syarat etis agar pendidikan agama tidak menjadi alat segregasi. Pendidikan agama yang inklusif mampu membangun dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman.
Sebaliknya, pendidikan agama yang eksklusif berpotensi menciptakan polarisasi. Polarisasi ini dapat menghambat kohesi sosial dan memperlemah semangat kebersamaan. Ketika pendidikan agama hanya menekankan superioritas satu kelompok, maka ruang untuk saling memahami menjadi sempit. Akibatnya, peserta didik tidak terbiasa berdialog dengan perbedaan, melainkan cenderung menolak atau menghindarinya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan interfaith menjadi relevan dan mendesak. Pendekatan ini menekankan pentingnya perjumpaan lintas iman sebagai bagian dari proses pembelajaran. Di satu sisi, perjumpaan ini membuka ruang untuk pengenalan formal terhadap tradisi lain. Di sisi lain, ia menjadi jalan untuk melahirkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai universal. Melalui dialog antar iman, peserta didik belajar bahwa kebenaran tidak bersifat tunggal dan tertutup, melainkan terbuka dan dapat diperkaya melalui pengalaman spiritual yang beragam.
Di titik ini, pendidikan agama yang inklusif tidak hanya berkutat di seputaran tataran metodologis namun merangkul juga komitmen etis. Komitmen ini menuntut guru agama untuk menjadi fasilitator dialog. Komitmen itu selangkah lebih jauh dari posisi guru agama sebagai ‘penjaga doktrin’ semata. Ketika peserta didik diajak untuk memahami iman orang lain dengan empati dan keterbukaan, maka pendidikan agama benar-benar menjadi ruang pembentukan karakter yang utuh yang merangkum karakteristik peserta didik yang beriman, berakal budi, dan berbelarasa.
Paul Knitter, seorang teolog dari Union Theological Seminary, menyatakan bahwa “dialog antar agama bukan hanya tentang toleransi, tetapi tentang transformasi.” Dalam terang pemikiran Knitter, pendidikan agama harus membuka ruang bagi peserta didik untuk mengalami perubahan perspektif. Perubahan ini terjadi melalui pengenalan terhadap nilai-nilai iman lain yang bersifat konstruktif. Pendidikan agama yang inklusif tidak menghapus identitas, tetapi memperkaya pemahaman terhadap identitas orang lain.
Pemikiran serupa dikemukakan oleh Raimon Panikkar, seorang filsuf dan teolog lintas tradisi. Panikkar menegaskan bahwa “kebenaran tidak dimonopoli oleh satu tradisi.” Ia mengusulkan pendekatan dialogik dalam pendidikan agama. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk melihat kebenaran sebagai proses yang terbuka. Pendidikan agama yang inklusif harus menghindari klaim absolut. Klaim ini dapat menutup ruang dialog dan menghambat pertumbuhan spiritual.
Dalam tradisi Islam, pemikiran inklusif tercermin dalam gagasan Prof. Nurcholish Madjid. Ia menekankan bahwa “agama harus menjadi sumber kedamaian, bukan sumber konflik.” Menurutnya, pendidikan agama harus mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan dan menumbuhkan semangat ‘ukhuwah insaniyah’ yaitu persaudaraan antar manusia. Pendidikan agama yang eksklusif, menurut Madjid, berisiko melahirkan sikap superioritas yang bertentangan dengan semangat tauhid yang memuliakan semua ciptaan.
Dari tradisi Buddhis, Thich Nhat Hanh, seorang guru Zen dan aktivis perdamaian, menyatakan bahwa “pemahaman adalah dasar dari cinta.” Ia mendorong praktik pendidikan spiritual yang berakar pada kesadaran dan empati. Dalam konteks pendidikan agama, pendekatan ini mengajak peserta didik untuk tidak hanya memahami ajaran sendiri, tetapi juga mendengarkan dengan hati terbuka ajaran dari tradisi lain. Pendidikan agama yang inklusif menurut Hanh adalah pendidikan yang membebaskan dari ketakutan dan kebencian terhadap yang berbeda.
Pendidikan agama yang inklusif merupakan pendekatan pedagogis yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut mencakup kasih, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai prinsip dasar dalam interaksi sosial dan spiritual. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini menjadi landasan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya religius, tetapi juga berempati dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan agama yang inklusif harus dirancang untuk menumbuhkan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.
Perancangan kurikulum pendidikan agama yang inklusif memerlukan pemahaman terhadap konteks sosial peserta didik. Konteks ini meliputi latar belakang budaya, agama, dan pengalaman hidup yang membentuk cara pandang dan respons peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kurikulum yang responsif terhadap keragaman ini akan mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru agama memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang menciptakan ruang belajar yang aman, terbuka, dan dialogis.
Inklusivitas dalam pendidikan agama tidak dapat dipahami semata sebagai pendekatan metodologis. Inklusivitas merupakan komitmen etis yang menuntut konsistensi dalam praktik pembelajaran. Praktik ini mencakup penggunaan sumber belajar lintas tradisi, pengembangan refleksi kritis terhadap nilai-nilai keagamaan, serta fasilitasi dialog antar peserta didik yang berbeda latar belakang. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk memahami iman secara kontekstual dan terbuka terhadap perspektif lain.
Sampai di titik ini, pendidikan agama yang inklusif dapat dimaknai sebagai jalan sunyi yang menuntun manusia menuju perjumpaan yang otentik dengan sesama dan dengan Yang Transenden. Ia bukan sekadar instrumen pedagogis, melainkan ruang batin tempat nilai-nilai kemanusiaan berakar dan tumbuh. Dalam ruang ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang Tuhan, tetapi juga belajar menjadi manusia yang utuh yang mampu merangkul perbedaan tanpa kehilangan jati diri.
Pendidikan agama yang inklusif membekali peserta didik bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan keberanian untuk mencintai dalam keberagaman. Ia membentuk karakter yang tidak gentar menghadapi keragaman, tetapi justru menemukan makna di dalamnya. Dalam keberagaman, peserta didik belajar bahwa damai bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kehadiran kasih yang melampaui batas-batas identitas.
Ketika nilai-nilai inklusif diinternalisasi, pendidikan agama menjelma menjadi proses transformatif. Ia tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga memperluas cakrawala spiritual. Cakrawala ini tidak dibatasi oleh dogma, melainkan dibuka oleh dialog. Dalam dialog, peserta didik menemukan bahwa kebenaran bukan milik satu suara, tetapi gema dari banyak suara yang saling mendengarkan.
Dengan demikian, pendidikan agama yang inklusif adalah nyala kecil dalam lorong zaman. Ia menyalakan harapan bahwa manusia dapat hidup berdampingan dalam damai, saling menghormati dalam iman, dan saling mengasihi dalam kemanusiaan. Di sanalah pendidikan menjadi ziarah, dan ziarah menjadi pembebasan.***
Anselmus Dore Woho Atasoge_Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
Apa Reaksi Anda?
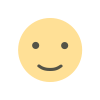 Suka
0
Suka
0
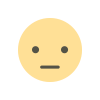 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
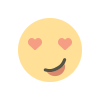 Cinta
0
Cinta
0
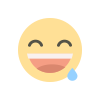 Lucu
0
Lucu
0
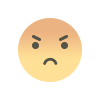 Marah
0
Marah
0
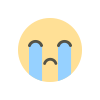 Sedih
0
Sedih
0
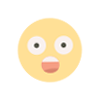 Wow
0
Wow
0