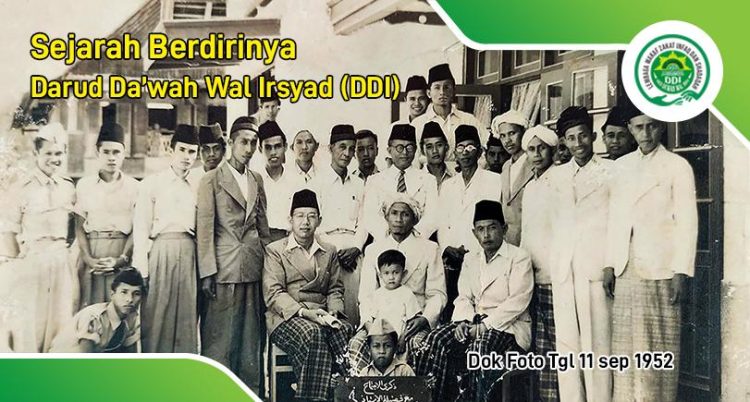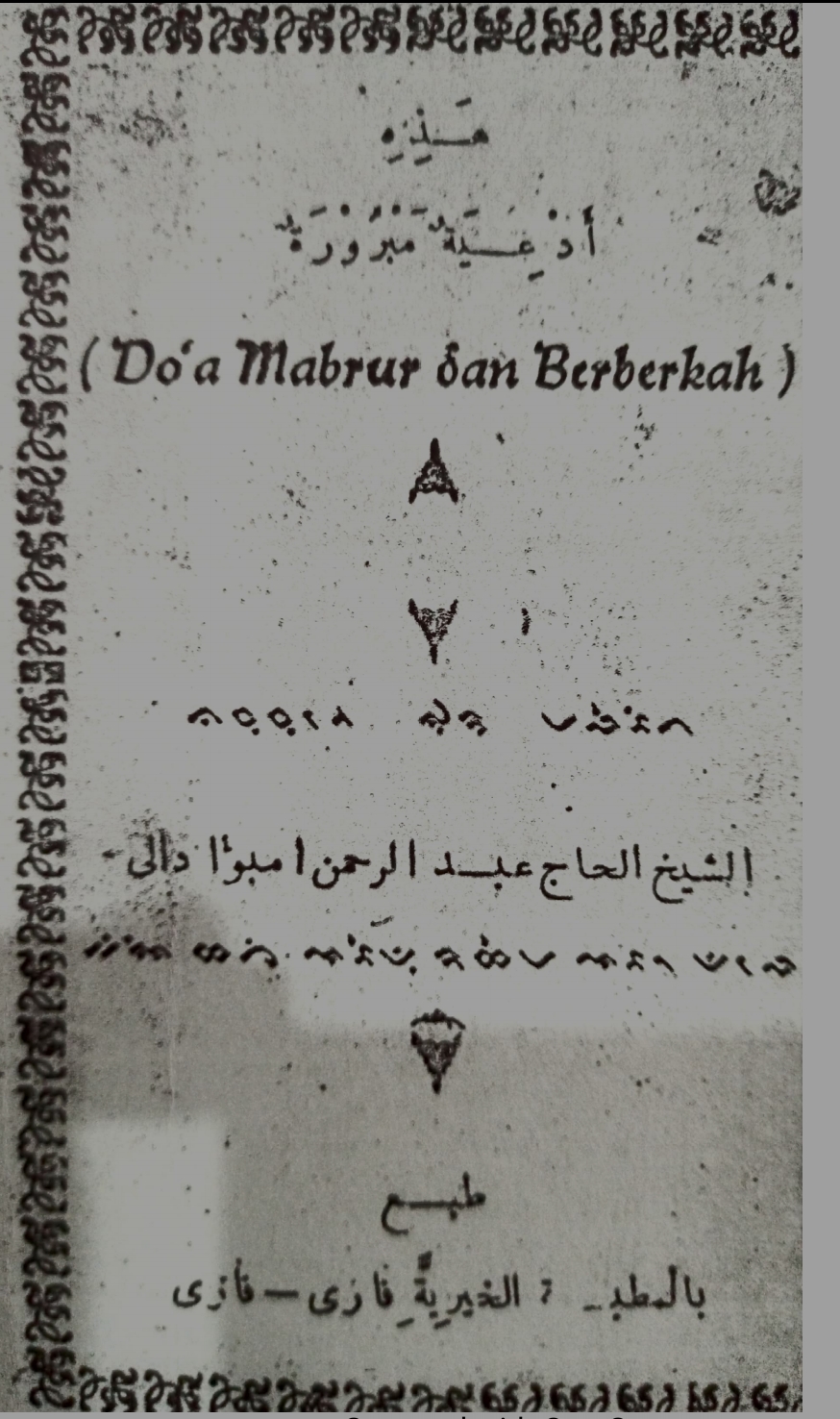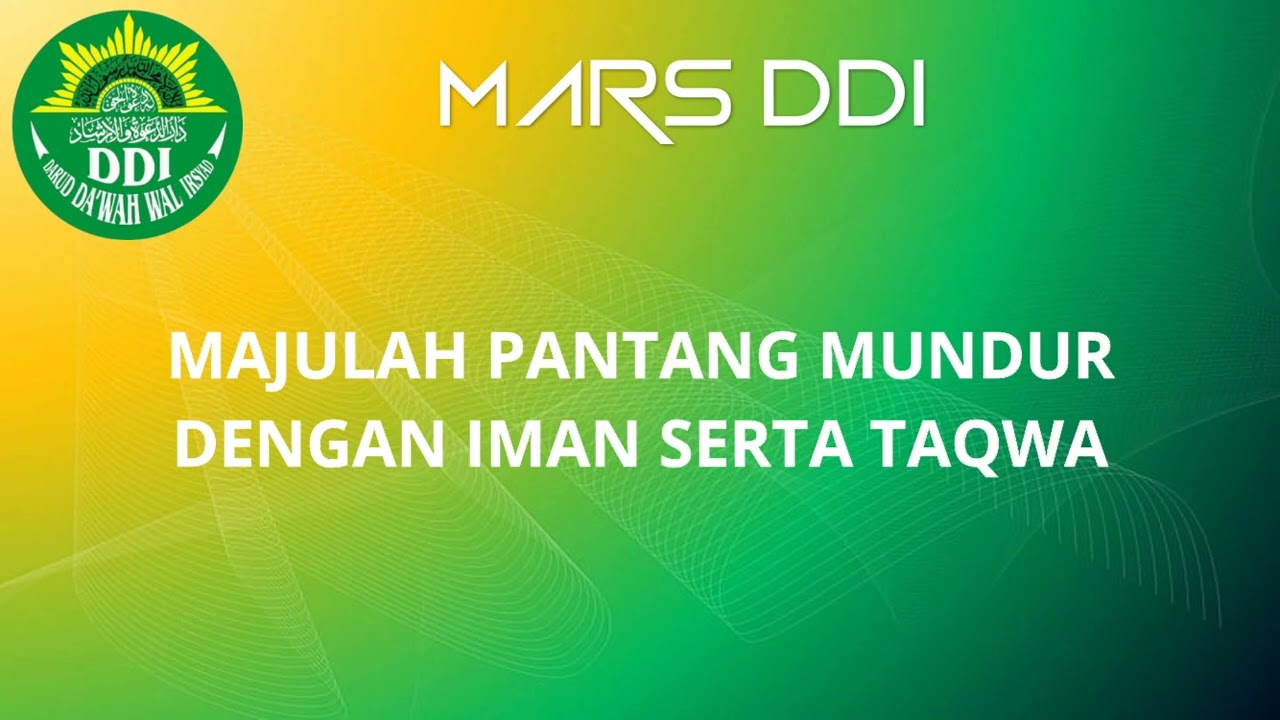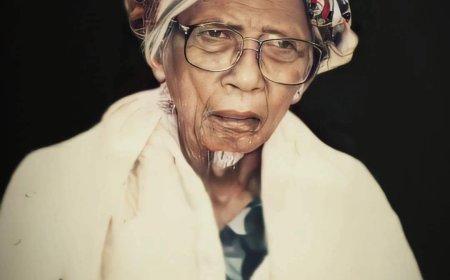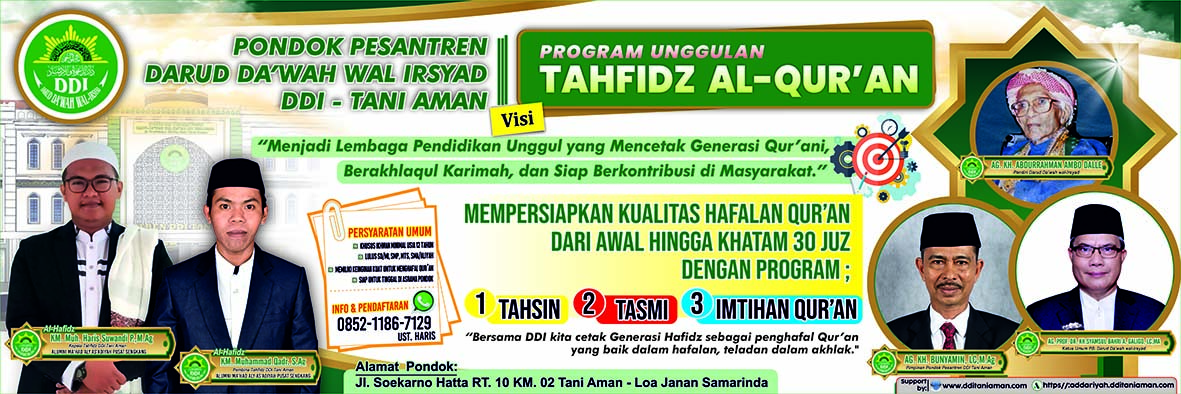Akhlak Demonstrasi (Perspektif Interfaith)

Demonstrasi merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi sebagai sarana rakyat menyuarakan aspirasi. Namun, ketika demonstrasi berubah menjadi ajang kekerasan, maka bukan hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan beragama. Kekerasan dalam demonstrasi mencederai martabat manusia dan merusak ruang publik sebagai tempat dialog dan transformasi sosial.
Dalam perspektif Islam, prinsip amar ma’ruf nahi munkar mendorong umat untuk menyampaikan kebenaran dan menolak kemungkaran. Namun, cara penyampaian harus berlandaskan adab dan damai. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Anwar Iskandar menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin konstitusi, tetapi harus dilakukan dengan akhlak dan etika. Ia menyayangkan demonstrasi yang berubah menjadi penjarahan dan kekerasan, karena menurutnya hal itu mencerminkan kesenjangan pemahaman tentang kebebasan yang bertanggung jawab.
Dalam tradisi Kristiani, Yesus Kristus mengajarkan bahwa cinta dan pengampunan lebih kuat daripada pedang. Pendeta Jacklevyn Manuputty, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menyatakan bahwa demonstrasi harus menjadi ruang ekspresi yang bermartabat, bukan ajang kekerasan. Ia menekankan pentingnya dialog antara rakyat dan pemimpin, serta menolak gaya hidup arogan dan kebijakan yang menindas. Kekerasan, menurutnya, bukan hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mencederai spiritualitas bangsa.
Sejalan dengan semangat Kristiani yang menolak kekerasan, Gereja Katolik menegaskan bahwa setiap tindakan brutal adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan nilai-nilai Injil yang menjunjung kasih dan keadilan. Paus Fransiskus, dalam berbagai pesan profetisnya, menyerukan agar protes sosial menjadi nyala harapan, bukan bara kebencian. Ia mengingatkan bahwa kekerasan bukan hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi justru memperpanjang luka, memperdalam jurang ketidakpercayaan, dan mengaburkan wajah kemanusiaan yang seharusnya bersinar dalam solidaritas. Dalam pandangan Gereja, perubahan sejati lahir dari keberanian untuk mencintai dalam situasi sulit, bukan dari amarah yang membakar jembatan dialog.
Ajaran resmi Gereja, seperti tertuang dalam Gaudium et Spes dan Kompendium Ajaran Sosial Gereja, menegaskan kekerasan tidak pernah menjadi solusi yang sah. Sebaliknya, perdamaian, kasih, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah jalan yang harus ditempuh dalam menyuarakan keadilan. Akan hal ini dapatlah dikatakan bahwa demonstrasi yang bermoral dari perspektif Katolik adalah demonstrasi yang mengedepankan kasih, kesaksian iman, dan keberanian untuk berdiri di pihak yang tertindas tanpa merusak tatanan sosial.
Sementara itu, ajaran Hindu dan Buddha menempatkan ahimsa (jalan tanpa kekerasan) sebagai prinsip utama dalam menghadapi konflik. Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, mengingatkan pentingnya mendengarkan suara hati dan suara rakyat dengan penuh ‘welas asih’. Ia menyerukan agar aspirasi disampaikan dalam bingkai kebenaran dan kasih sayang, bukan dengan amarah dan perusakan. Dalam Buddhisme, kekerasan dianggap sebagai bentuk kebodohan spiritual yang menghalangi pencerahan dan kedamaian batin.
Indonesia kaya akan tradisi-tradisi lokal yang juga mengajarkan tentang resolusi damai, menjadikannya sumber kearifan yang relevan dalam menghadapi konflik sosial masa kini. Di Maluku, falsafah Satu Tungku Tiga Batu menjadi simbol hidup berdampingan antara tiga agama besar (Kristen, Islam, dan Katolik) dalam satu komunitas, di mana setiap “batu” menopang “tungku” kehidupan bersama, menekankan pentingnya keseimbangan dan saling menghormati dalam keberagaman. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, upacara adat Tiwah yang melibatkan berbagai komunitas lintas agama dan etnis bukan hanya ritual pemurnian arwah, tetapi juga ruang rekonsiliasi sosial, di mana masyarakat berkumpul untuk memperkuat solidaritas dan menghindari konflik antar kelompok.
Tradisi-tradisi semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai damai telah lama tertanam dalam budaya lokal Indonesia, dan dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Karena itu, ketika demonstrasi melupakan akar budaya dan tradisi-tradisi baik yang dimiliki bangsa ini, maka ia kehilangan makna sebagai ritual sosial yang bermoral dan yang mengarah kepada tujuan yang membebaskan.
Demonstrasi yang bermoral adalah demonstrasi yang menjunjung nilai-nilai spiritual dan budaya: keberanian menyuarakan kebenaran, kesediaan mendengar yang berbeda, dan komitmen menjaga kedamaian. Ketika negara merespons dengan kekerasan, atau ketika demonstran melampiaskan frustrasi dengan merusak, maka keduanya telah gagal memahami bahwa perubahan sejati lahir dari kesadaran, bukan kebencian.
Agama-agama dan tokoh-tokohnya mengingatkan bahwa suara rakyat harus didengar dengan hati, bukan ditakuti dengan senjata. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, spiritualitas lintas iman bisa menjadi jembatan untuk membangun ruang publik yang lebih manusiawi. Di dalamnya, demonstrasi menjadi panggilan nurani, bukan medan pertempuran.***
Anselmus Dore Woho Atasoge (Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)
Apa Reaksi Anda?
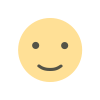 Suka
0
Suka
0
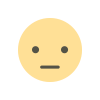 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
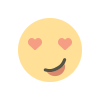 Cinta
0
Cinta
0
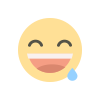 Lucu
0
Lucu
0
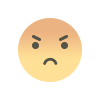 Marah
0
Marah
0
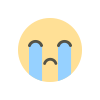 Sedih
0
Sedih
0
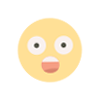 Wow
0
Wow
0