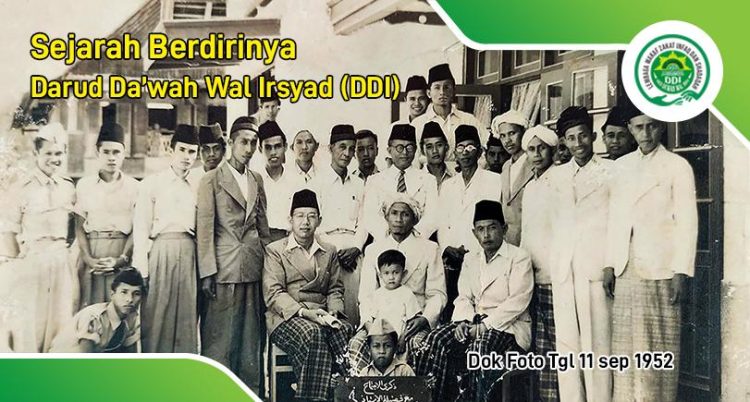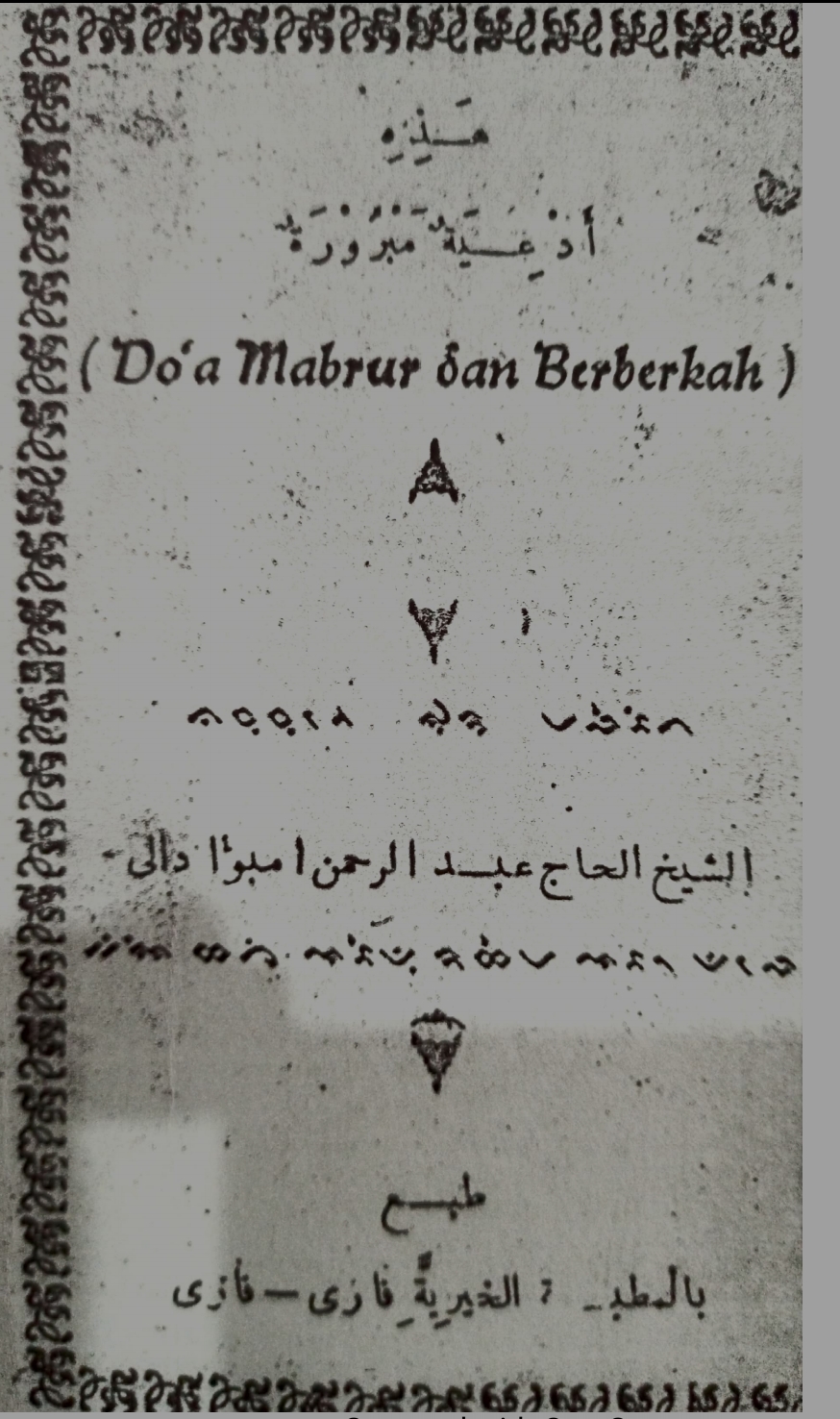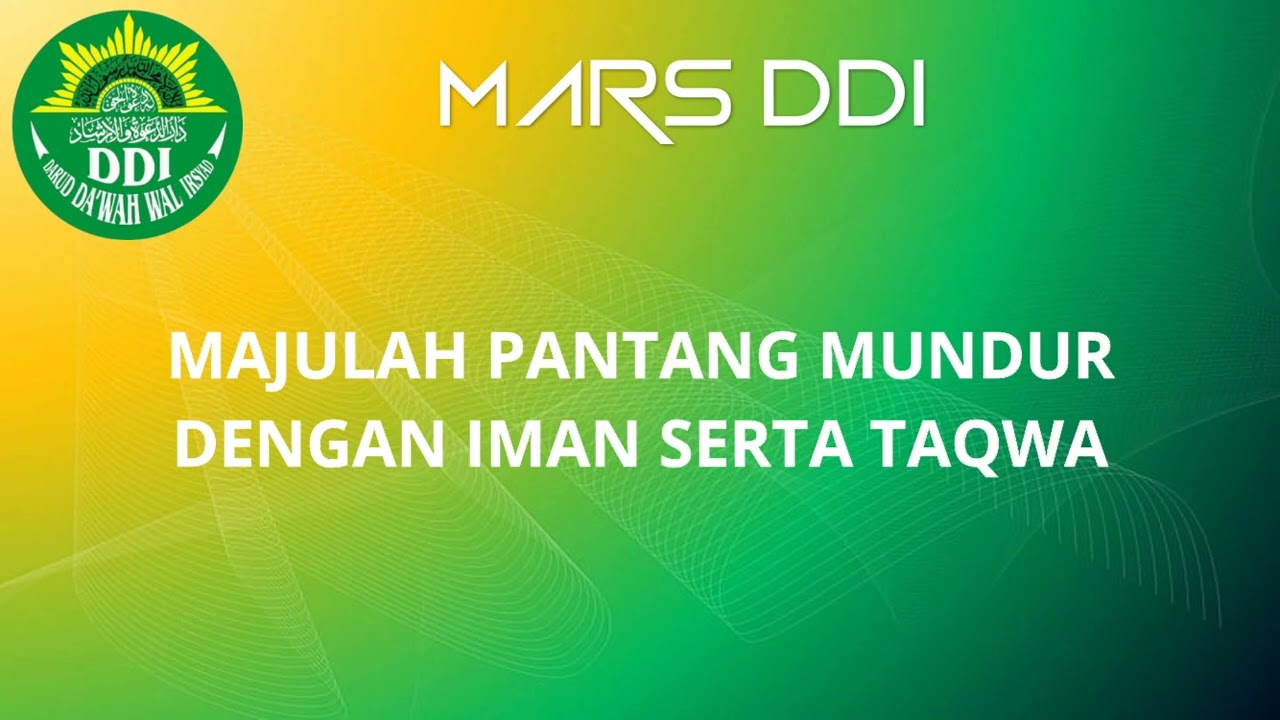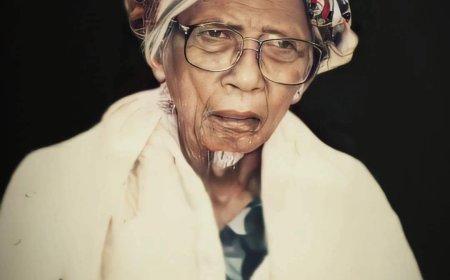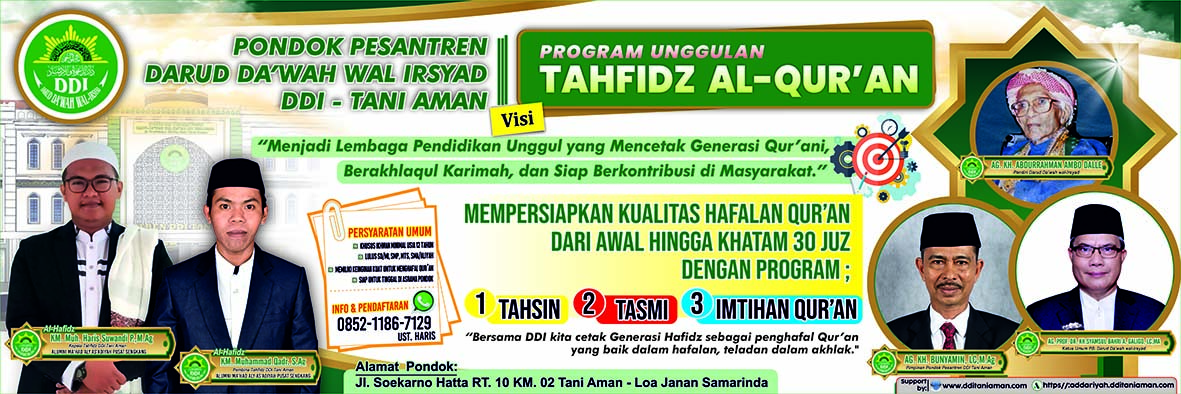Epistemologi Kebangsaan: Membaca Sumpah Pemuda lewat Pendidikan

Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa ini, Sumpah Pemuda bukanlah sekadar peristiwa monumental yang tertulis dalam buku teks. Sumpah Pemuda adalah denyut nadi dari kesadaran kolektif yang bangkiat dari jiwa-jiwa muda yang resah mencari makna “menjadi Indonesia”. Tiga ikrar sederhana—tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu—menjadi fondasi ontologis bagi keindonesiaan kita, sekaligus cermin dari upaya pencarian pengetahuan tentang diri dan bangsa. Dalam konteks ini, Sumpah Pemuda bukan hanya simbol nasionalisme, melainkan epistemologi, cara bangsa ini memahami dirinya melalui kesadaran pendidikan.
Epistemologi kebangsaan adalah cara bangsa menafsirkan pengetahuan, bukan sekadar akumulasi data dan teori, melainkan kesadaran yang tumbuh dari akar budaya, nilai, dan sejarah. Pendidikan menjadi ruang di mana epistemologi itu dihidupkan. Namun, di era modern ini, pendidikan kerap kehilangan maknanya sebagai laku pembebasan. Pendidikan tergelincir menjadi sekadar sistem transmisi informasi, bukan pengasuhan jiwa. Di ruang-ruang kelas, murid-murid dihadapkan pada angka dan ranking, bukan pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang siapa dirinya sebagai anak bangsa.
Pendidikan yang Membebaskan
Filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara memberi kita jalan terang, yakni memandang pendidikan sebagai “tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak,” bukan paksaan, bukan penyeragaman, melainkan pendampingan agar manusia mencapai kemerdekaan lahir dan batin. Inilah epistemologi pendidikan yang lahir dari bumi sendiri, yakni berakar pada kebudayaan, tumbuh dari kearifan lokal (local wisdom), dan berbuah pada kemanusiaan universal (humanisme universal). Dalam bingkai ini, Sumpah Pemuda dapat dibaca sebagai ikrar epistemologis, yakni janji untuk mengenal dan mencintai pengetahuan melalui identitas Indonesia.
Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa menjadi bangsa bukanlah hasil pemberian, melainkan hasil pembelajaran. Kesadaran “bertanah air satu” adalah pelajaran tentang kebersamaan ruang; “berbangsa satu” adalah pelajaran tentang tanggung jawab moral; dan “berbahasa satu” adalah pelajaran tentang komunikasi makna. Ketiganya menjadi kurikulum batin yang seharusnya diajarkan sejak dini di setiap sekolah, bukan hanya lewat upacara, tapi lewat cara berpikir, bertutur, dan bertindak.
Namun kini, pendidikan kita tengah dihadapkan pada krisis makna. Ketika kecerdasan buatan (AI) menggantikan banyak fungsi kognitif manusia, pertanyaan mendasar muncul: apakah kita masih mendidik manusia, atau sekadar melatih mesin yang berwujud manusia? Sumpah Pemuda yang lahir dari semangat kebersamaan kini diuji oleh individualisme digital, oleh kompetisi yang membutakan solidaritas, oleh globalisasi yang mengikis identitas. Di tengah arus itu, epistemologi kebangsaan harus menjadi jangkar.
Filsafat pendidikan Paulo Freire berbicara tentang pendidikan sebagai praksis pembebasan, pendidikan yang memanusiakan manusia. Paulo Freire menolak model pendidikan “gaya bank” dan menggantinya dengan dialog, kesadaran kritis, dan pembebasan. Jika dipertemukan dengan semangat Sumpah Pemuda, maka pendidikan Indonesia seharusnya menjadi jalan untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan ketakberdayaan, agar mampu berdikari sebagai subjek dalam sejarahnya sendiri.
Di ruang kelas, misalnya, seorang guru yang tidak hanya mengajar rumus, tetapi mengajak murid merenungkan makna kemerdekaan belajar, sesungguhnya sedang menghidupkan semangat Sumpah Pemuda. Saat siswa diajak berdiskusi tentang mengapa mereka perlu belajar bahasa Indonesia di tengah derasnya hegemoni bahasa asing, itu bukan sekadar pelajaran linguistik, melainkan pelajaran identitas. Mereka sedang belajar mencintai bahasa sebagai ruang berpikir dan berbangsa.
Falsafah hidup Indonesia mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, antara individu dan komunitas, antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Nilai-nilai gotong royong, hormat, dan tanggung jawab sosial bukan sekadar etika sosial, melainkan epistemologi, cara khas bangsa ini memahami dunia. Inilah yang membuat pendidikan di Indonesia tidak bisa diseragamkan dengan model Barat yang individualistik.
Jika dalam filsafat Barat kita mengenal adagium Descartes “aku berpikir maka aku ada”, maka keindonesiaan menegaskan “aku hidup bersama, maka aku manusia.” Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti belajar bukan sekadar proses personal, tetapi juga sosial-kultural. Sumpah Pemuda menjadi simbol dari kesadaran kolektif itu yakni pengetahuan yang tumbuh dari kebersamaan, bukan kesendirian.
Pendidikan Berbasis Kebangsaan
Di era modern, di mana pengetahuan dapat diakses dengan satu sentuhan layar, kita dihadapkan pada paradoks: semakin banyak tahu, tetapi semakin miskin makna. Di sinilah pendidikan berbasis kebangsaan menjadi penting, agar pengetahuan tidak tercerabut dari akar nilai. Sekolah, pesantren, universitas, dan lembaga pendidikan apapun harus kembali menjadi ruang kontemplasi, bukan sekadar pabrik ijazah dan sertifikat.
Contoh sederhana dapat kita lihat dalam praktik gotong royong di sekolah. Ketika siswa dan guru membersihkan lingkungan sekolah bersama, mereka tidak hanya belajar kebersihan fisik, tetapi juga belajar etika sosial, tanggung jawab, dan cinta lingkungan. Itu adalah bentuk nyata epistemologi kebangsaan, sebuah pengetahuan yang hidup dalam tindakan (psikomotorik), bukan hanya dalam hafalan (kognitif).
Begitu pula dalam pembelajaran sejarah. Jika sejarah hanya disampaikan sebagai deretan tanggal dan nama tokoh, maka akan kehilangan jiwa. Namun ketika guru mengajak murid berdialog tentang alasan pemuda tahun 1928 berani bersumpah satu bangsa, maka sejarah berubah menjadi cermin. Murid belajar berpikir kritis, sekaligus mencintai bangsa dengan kesadaran yang matang (afektif).
Dalam perspektif filsafat, pendidikan adalah medan dialektika antara masa lalu dan masa depan. Sebuah upaya memahami warisan sejarah untuk membangun masa depan yang manusiawi. Sumpah Pemuda memberi arah moral bahwa masa depan bangsa ini harus dibangun di atas dasar kesatuan dan kemanusiaan. Pendidikan yang berpihak pada kebangsaan berarti menanamkan kesadaran itu dalam setiap pelajaran dan pengalaman belajar.
Epistemologi kebangsaan tidak menolak modernitas, tetapi menafsirkan modernitas dengan metode tafsir sendiri. Dalam dunia pendidikan, ini berarti memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nurani, menguasai sains tanpa menanggalkan etika, dan membuka diri terhadap dunia tanpa kehilangan rasa tanah air. Falsafah Bhinneka Tunggal Ika menjadi panduan epistemologis yakni membaca perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman.
Falsafah Keindonesiaan
Setiap generasi muda adalah penerus semangat Sumpah Pemuda. Namun semangat itu tidak lahir dari seremoni tahunan, melainkan dari kesadaran yang ditanamkan melalui pendidikan yang memerdekakan atau membebaskan (liberasi). Ketika siswa belajar berpikir kritis, berempati, dan bekerja sama lintas budaya, mereka sedang melanjutkan ikrar kebangsaan dengan cara baru.
Di tengah krisis moral dan kebingungan identitas, pendidikan yang berakar pada falsafah hidup Indonesia dapat menjadi penawar. Kita perlu kembali pada falsafah sangkan paraning dumadi, yang dalam konteks pendidikan kita dilatih untuk mengenal siapa diri kita, dari mana asal kita, dan untuk apa kita belajar. Pendidikan yang demikian bukan hanya mencetak lulusan pintar, tetapi manusia yang bijak dan berjiwa matang.
Sumpah Pemuda, dalam kacamata epistemologi kebangsaan, adalah panggilan untuk menata ulang pengetahuan dalam kerangka keindonesiaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan sejati lahir dari cinta pada tanah air, cinta pada kemanusiaan, dan cinta pada kebenaran. Dalam dunia yang serba cepat dan bising, atau dalam istilah Yasraf Amir Piliang disebut sebagai “dunia yang berlari” ini, kita perlu kembali menenangkan diri dan bertanya seperti para pemuda 1928: siapa kita, dan untuk apa kita bersatu? Pendidikan harus menjadi ruang untuk menemukan jawaban itu, bukan menyalin jawaban orang lain.
Dengan begitu, kita akan sadar bahwa membaca Sumpah Pemuda lewat pendidikan adalah membaca diri sendiri. Kita diajak untuk menulis ulang makna belajar, bukan untuk sekadar mengejar gelar, tapi untuk memahami makna hidup berbangsa, sebagaimana dikatakan Rabindranath Tagore (Penyair sekaligus Filsuf India pemeroleh Hadiah Nobel Sastra tahun 1913)bahwa pendidikan bukan sekadar untuk mengejar gelar, melainkan untuk memperluas dan memperdalam wacana tentang hidup dan kehidupan. Maka, pendidikan yang berjiwa Sumpah Pemuda adalah pendidikan yang menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni cerdas, beradab, dan berakar pada cinta akan tanah airnya.
Dr. Dimas Indianto S.,M.Pd.I. (Budayawan, Peneliti, dan Dosen UIN Saizu Purwokerto)
Apa Reaksi Anda?
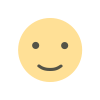 Suka
0
Suka
0
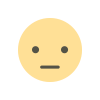 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
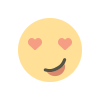 Cinta
0
Cinta
0
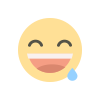 Lucu
0
Lucu
0
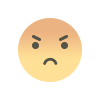 Marah
0
Marah
0
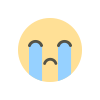 Sedih
0
Sedih
0
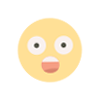 Wow
0
Wow
0