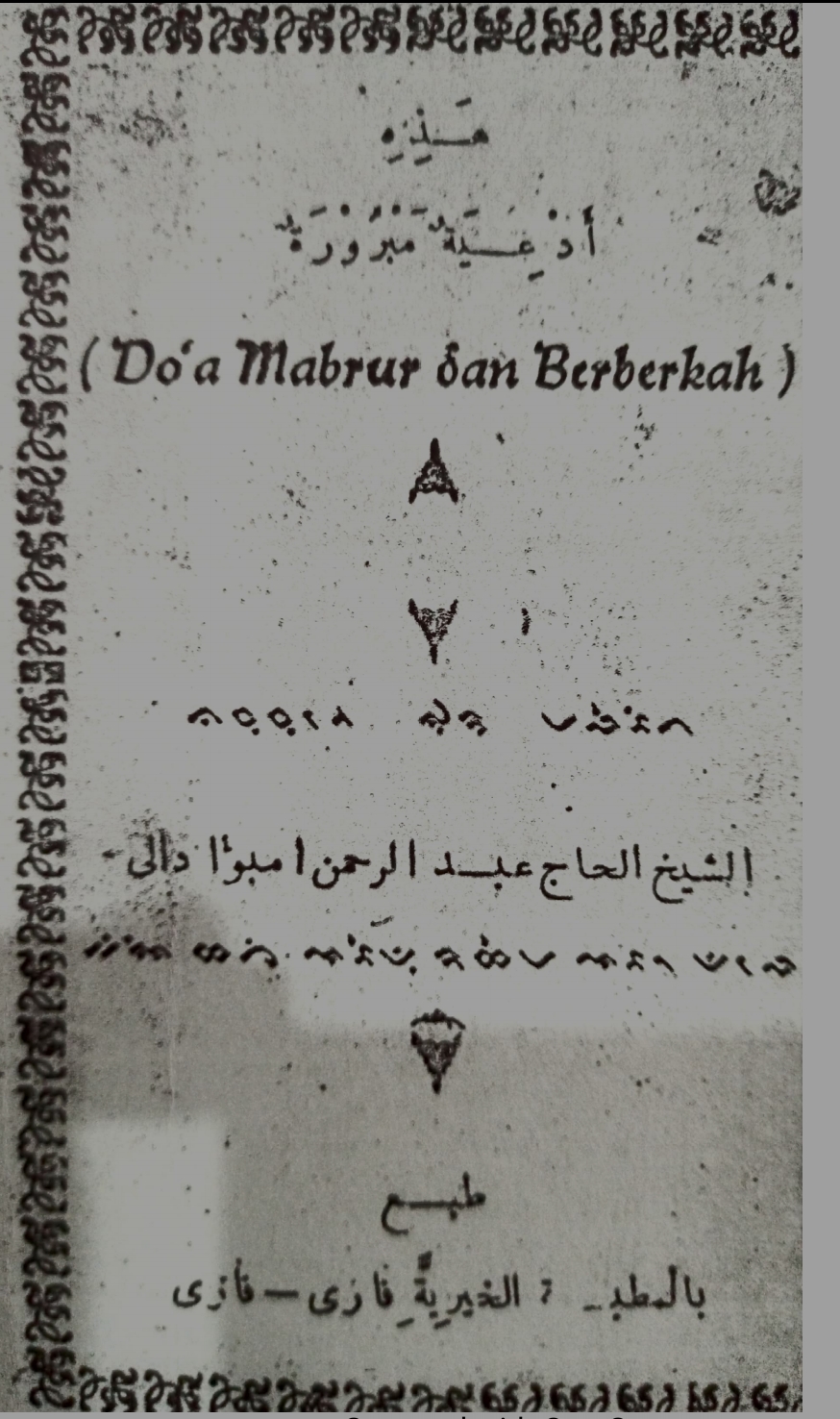Pendidikan Islam, Tradisi, dan Jalan Keilmuan yang Membumi

Di zaman ketika pendidikan cenderung didefinisikan oleh sertifikat, akreditasi, dan capaian teknis, kita perlu mengambil jarak sejenak dan bertanya ulang: untuk apa sebenarnya pendidikan itu? Apakah cukup hanya melahirkan lulusan yang trampil bekerja tetapi hampa kebijaksanaan? Apakah pendidikan berhenti pada penguasaan keterampilan dan pengumpulan angka indeks prestasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan kembali terutama dalam konteks pendidikan Islam. Sebab, pendidikan dalam tradisi Islam sejatinya bukan hanya soal transfer ilmu pengetahuan (ta’līm), tetapi juga pembentukan jiwa (tarbiyah) dan penyucian diri (tazkiyah). Pendidikan Islam yang asli bukan hanya tentang informasi, melainkan tentang transformasi.
Namun sayangnya, dalam praktiknya, pendidikan Islam sering kali tercerabut dari akarnya. Ia diposisikan sekadar sebagai satu model “alternatif” dalam sistem yang seragam. Nilai-nilai tradisi yang dahulu menghidupi pendidikan Islam pelan-pelan dikesampingkan demi efisiensi dan standarisasi. Padahal, justru dalam tradisi itulah nilai-nilai keilmuan yang membumi tumbuh dan mengakar.
Tradisi: Bukan Masa Lalu, Tapi Rasa yang Hidup
Kata "tradisi" dalam masyarakat modern sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang kolot, kuno, dan tidak relevan dengan kemajuan zaman. Padahal, dalam pandangan yang lebih jernih, tradisi bukanlah masa lalu yang harus ditinggalkan, melainkan kesadaran kolektif yang membentuk jati diri masyarakat. Ia adalah ingatan yang hidup, bukan fosil budaya. Tradisi adalah rasa yang turun-temurun, mewujud dalam etika, laku hidup, dan cara berpikir suatu komunitas.
Dalam konteks pendidikan Islam, tradisi memainkan peran sentral. Pendidikan berbasis pesantren misalnya, tumbuh dari rasa hormat kepada guru, kebersamaan dalam belajar, dan kontinuitas sanad keilmuan. Ada proses panjang dalam membentuk murid menjadi manusia yang utuh, bukan hanya karena ia hafal teks, tetapi karena ia mengalami laku.
Kita bisa belajar dari bagaimana para santri menghayati ilmu. Mereka tidak tergesa-gesa menyelesaikan kitab, tetapi sabar memahaminya. Mereka tidak hanya membaca, tetapi mengamalkan. Mereka tidak hanya duduk di kelas, tetapi terlibat dalam laku hidup bersama: memasak, membersihkan, menyambut tamu, berjamaah, semua itu menjadi bagian dari pendidikan. Inilah pendidikan yang membumi, yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga menyatu dengan tubuh dan jiwa.
Jalan Ilmu: dari Kitab menuju Laku
Dalam sejarah Islam klasik, pencarian ilmu adalah sebuah perjalanan ruhani. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibn ‘Arabi, dan Jalaluddin Rumi bukan hanya dikenal karena kedalaman pemikiran mereka, tetapi juga karena perjalanan panjang yang mereka tempuh, baik secara fisik maupun batin, untuk menemukan kebenaran.
Mereka tidak hanya berguru pada satu dua kitab, tetapi mengalami hidup di bawah bimbingan para guru. Proses ini melibatkan pembentukan karakter, pengasahan jiwa, dan pemurnian niat. Ilmu bukanlah sesuatu yang ditumpuk, tetapi sesuatu yang diresapi. Dalam tradisi keilmuan seperti ini, seseorang tidak layak berbicara tentang ilmu sebelum ia menjalaninya dalam laku.
Sayangnya, dalam dunia pendidikan hari ini, keilmuan lebih banyak diposisikan sebagai “kepemilikan” daripada jalan. Kita diajarkan untuk “menguasai” ilmu, bukan untuk “dikuasai” oleh hikmah yang dikandungnya. Kita diajarkan untuk cepat-cepat tampil, bukan sabar mengendapkan. Akibatnya, lahir generasi yang mungkin cakap secara teknis, tetapi rapuh secara mental dan spiritual.
Adab Sebelum Ilmu
Salah satu prinsip paling penting dalam pendidikan Islam klasik adalah adab sebelum ilmu. Seorang murid harus memiliki akhlak yang baik sebelum dinilai cerdas atau pintar. Dalam banyak kisah ulama terdahulu, kita sering mendengar bahwa mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk melayani guru, mengamati perilakunya, dan meneladani akhlaknya, sebelum akhirnya diizinkan membaca atau mengajarkan kitab.
Prinsip ini sejatinya adalah bentuk pendidikan yang membumi. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menyelesaikan persoalan tidak hanya ditentukan oleh logika atau ilmu yang dikuasai, tetapi oleh sikap, ketulusan, dan kearifan. Sayangnya, nilai adab ini kian pudar dalam sistem pendidikan yang lebih menekankan capaian akademik daripada pembentukan karakter.
Pendidikan yang membumi mengajarkan bahwa mengetahui belum tentu menjadi mengerti. Mengerti belum tentu menjadi bijaksana. Dan kebijaksanaan tidak bisa diajarkan secara langsung, ia harus ditumbuhkan dalam relasi antarmanusia yang jujur, sabar, dan berkesinambungan.
Membumikan Kembali Pendidikan Islam
Dalam situasi sekarang, ada dua jalan ekstrem yang sedang diambil oleh lembaga pendidikan Islam: satu yang terlalu terobsesi dengan sertifikasi dan modernisasi administratif, dan satu lagi yang terlalu mengidealkan romantisme masa lalu tanpa kemampuan menjawab tantangan kontemporer. Keduanya tidak cukup. Kita membutuhkan pendidikan Islam yang berakar dan terbuka; yang membumi sekaligus melangit.
Membumikan pendidikan Islam berarti membawanya kembali kepada kehidupan konkret. Ia tidak boleh terjebak hanya dalam ruang kelas atau podium seminar, tetapi hadir dalam kerja-kerja sosial, dalam kebudayaan, dalam praktik hidup harian. Ilmu tidak boleh berhenti menjadi teori, tetapi harus menjelma menjadi laku: laku peduli, laku berbagi, laku memperbaiki.
Untuk itu, tradisi harus dihidupkan kembali bukan sekadar sebagai warisan, tetapi sebagai sumber daya spiritual dan intelektual. Pendidikan Islam tidak harus menolak teknologi atau kemajuan, tetapi harus memiliki akar agar tidak terseret arus. Tradisi adalah jangkar yang menjaga arah perahu agar tidak karam.
Jalan Pulang Melalui Ilmu
Pendidikan Islam yang membumi bukanlah konsep ideal yang utopis. Ia pernah ada, hidup, dan membentuk peradaban. Tugas kita hari ini bukan menciptakan sistem baru dari nol, tetapi menggali kembali akar yang pernah memberi kehidupan. Merekam ulang jejak para guru, para pejalan, para pencari ilmu yang hidupnya bukan untuk tampil, tetapi untuk menyampaikan hikmah.
Di tengah zaman yang serba cepat dan kompetitif, kita membutuhkan pendidikan yang menuntun manusia untuk kembali menjadi manusia: yang lembut, sadar akan dirinya, dan berserah kepada Tuhan. Itulah pendidikan Islam yang sesungguhnya, yang bertradisi, berjiwa, dan membumi.***
Abdul Wachid B.S. (Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)
Apa Reaksi Anda?
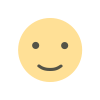 Suka
0
Suka
0
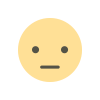 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
 Cinta
0
Cinta
0
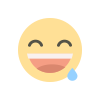 Lucu
0
Lucu
0
 Marah
0
Marah
0
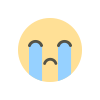 Sedih
0
Sedih
0
 Wow
0
Wow
0