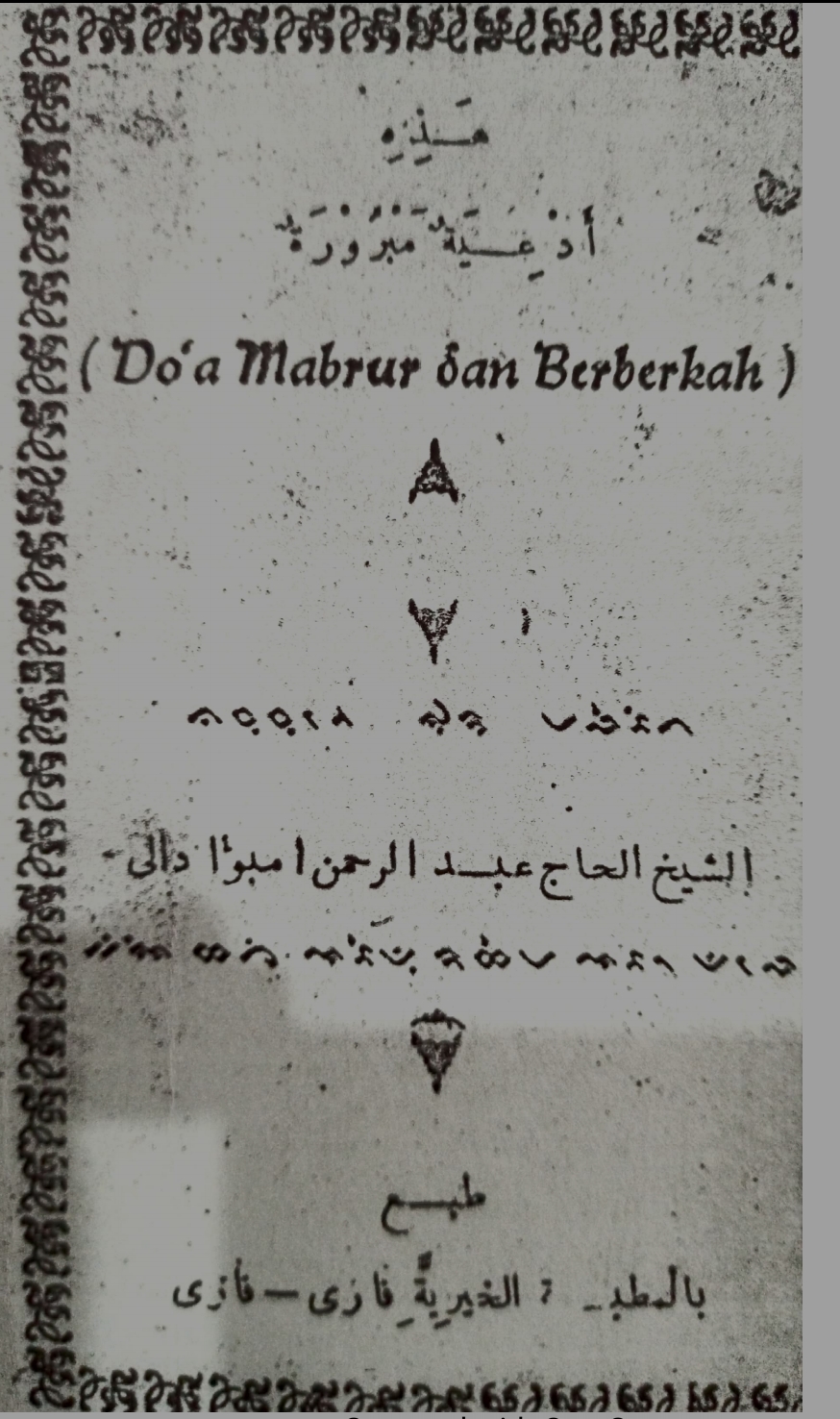Maulid Nabi: antara Keteladanan dan Kenyataan

Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. Persis, maulid selalu datang dengan cara yang hampir sama: pengajian, doa bersama, gema salawat di masjid-masjid. Tapi mungkin kita lupa, ia sesungguhnya bukan sekadar hari peringatan. Ia adalah semacam pengingat tentang hadirnya seorang manusia yang tak pernah lelah mencintai, seorang manusia yang lahir di tengah padang pasir yang tandus, di sebuah masyarakat yang porak-poranda oleh perang, dendam, dan kesenjangan. Dari rahim itu, Muhammad lahir. Berdasar tutur Sejarah, ia bukanlah raja, bukan pula seorang bangsawan, tapi anak yatim yang kelak mengubah dan menata dunia.
Kita mungkin bertanya, apa artinya Maulid di negeri kita hari ini? Kita tahu, Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada retakan di dalamnya akibat ketidakpercayaan terhadap kekuasaan: mahasiswa yang turun ke jalan, demonstrasi yang meledak menjadi kerusuhan, fasilitas umum yang hancur dan rumah yang dijarah. Dan di layar kaca, kita melihat pemimpin yang menantang warganya. Menampilkan gaya hidup seolah tak peka pada derita warga. Atau, yang berjanji tapi lupa untuk memenuhi.
Keadilan
Menurut kisah sejarah, Nabi tak pernah berjarak dengan masyarakatnya. Ia makan bersama orang miskin, ia menambal sandalnya sendiri, ia tak segan mendengar keluhan mereka yang tak diperhitungkan. Bahkan di Madinah, ia menulis Piagam yang melindungi semua orang, Muslim dan bukan Muslim, dengan satu bahasa yang sama: keadilan!
Kini, kita hidup dalam situasi sosial politik yang mudah sekali terjebak pada citra. Lebih sibuk membangun panggung daripada menumbuhkan kepercayaan. “Tanamkan dirimu di tanah kerendahan, sebab yang tumbuh tanpa tanah itu akan rapuh,” begitu kata Ibn ‘Athaillah suatu ketika. Tapi kerendahan hati sering menguap begitu saja di tengah-tengah keramaian kekuasaan.
Di tepi lain, kita kerap menyaksikan bagaimana isu agama dijadikan alat perebutan suara, bagaimana perbedaan dijadikan jurang, bukan jembatan. Kita menyaksikan praktik korupsi, nepotisme, dan transaksi yang berlangsung di balik pintu. Di hadapan semua itu, peringatan Maulid yang kita selenggarakan seakan hanya jadi gema yang jauh dan tak menyentuh. Padahal, Nabi datang justru untuk menutup luka itu: menghadirkan amanah, mencontohkan kejujuran, menegaskan kasih sayang.
Konon Rumi pernah menulis, “Jadilah seperti mata air yang memberi, bukan kendi yang hanya menampung.” Saya kira, kata-kata Rumi ini adalah cermin dari laku dan tindak-tanduk Nabi. Tapi hari ini kita menyaksikan sebaliknya, pemimpin yang seolah menampung, menimbun, menutup rapat sumber daya yang seharusnya mengalir sampai jauh. Kita seperti berjalan di tepi sungai yang kering, mendengar suara gemericik yang tinggal kenangan.
Keteladanan
Maulid yang kita peringati, jika dibaca dengan hati, sejatinya adalah undangan untuk menoleh kembali: apa yang kita rayakan sebenarnya? Apakah sekadar kelahiran yang kita hias dengan spanduk dan pengeras suara? Ataukah kita benar-benar merayakan teladan yang seharusnya hidup dalam diri para pemimpin?
Mungkin kita harus jujur pada diri sendiri: betapa sering kita merayakan Maulid Nabi, tapi melupakan nilai yang beliau bawa. Kita bersholawat menyebut namanya, tapi tak meniru laku hidupnya. Kita menyalakan lampu-lampu di panggung Maulid, tapi lupa pada cahaya yang seharusnya hadir dalam keseharian: cahaya kejujuran, cahaya kasih, cahaya kerendahan hati.
Maulid bukan sekadar seremonial, tapi cermin. Dan cermin itu bisa kejam: ia memantulkan wajah kita apa adanya. Di dalamnya, kita mungkin melihat bahwa bangsa ini semakin jauh dari teladan Nabi. Bahwa kekuasaan yang dijalankan bukan sebagai amanah, tapi sebagai kesempatan. Bahwa pemimpin lebih suka dihormati daripada merendah.
Tapi barangkali justru di situ arti Maulid: ia semacam momen untuk mengingatkan, di tengah kegelapan, selalu ada cahaya yang mungkin hadir. Cahaya itu mungkin saja terasa jauh, tapi bayangannya selalu dekat, menunggu untuk ditangkap kembali.
Maka boleh jadi, dalam keheningan Maulid nabi, kita diajak untuk merenung: adakah kita, sebagai bangsa, sungguh-sungguh menelusuri jejak Nabi? Atau hanya merayakan kelahirannya sambil membiarkan teladannya terkubur oleh riuh pesta?
Barangkali, jawaban itu ada di wajah rakyat yang lapar, di suara para demonstran yang serak, di reruntuhan fasilitas umum yang terbakar, dan di rumah yang dijarah. Dan mungkin, di dalam hati kita yang lirih, masih ada doa yang tak pernah lelah kita panjatkan: semoga kita menemukan kembali makna kepemimpinan sebagaimana pernah dicontohkan seorang yatim yang lahir lebih dari seribu empat ratus tahun lalu. Allahu a’lam bi-Shoawab.
Radea Yuli Ahmad Hambali (Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Apa Reaksi Anda?
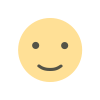 Suka
0
Suka
0
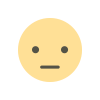 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
 Cinta
0
Cinta
0
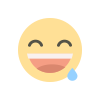 Lucu
0
Lucu
0
 Marah
0
Marah
0
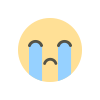 Sedih
0
Sedih
0
 Wow
0
Wow
0