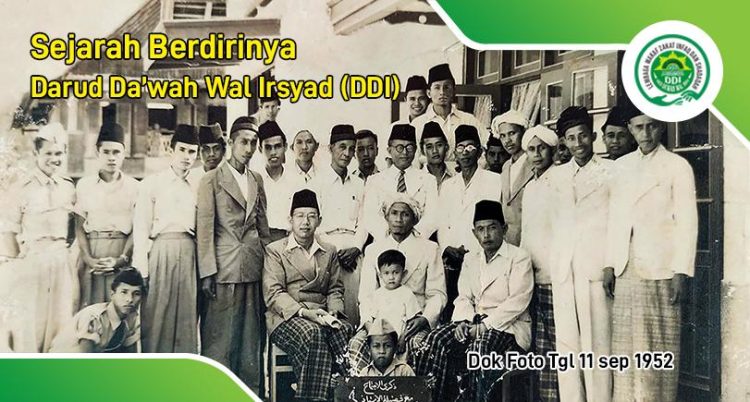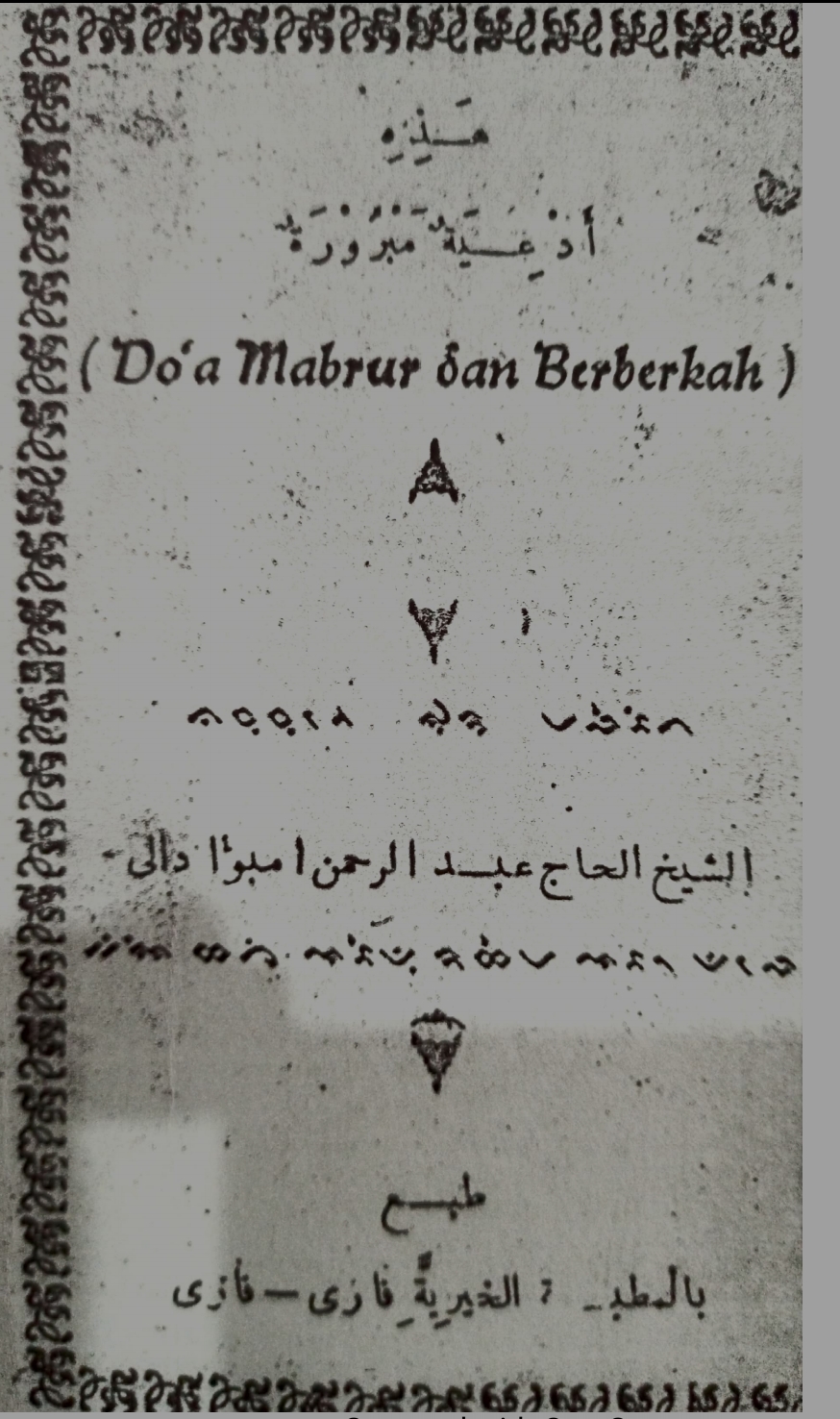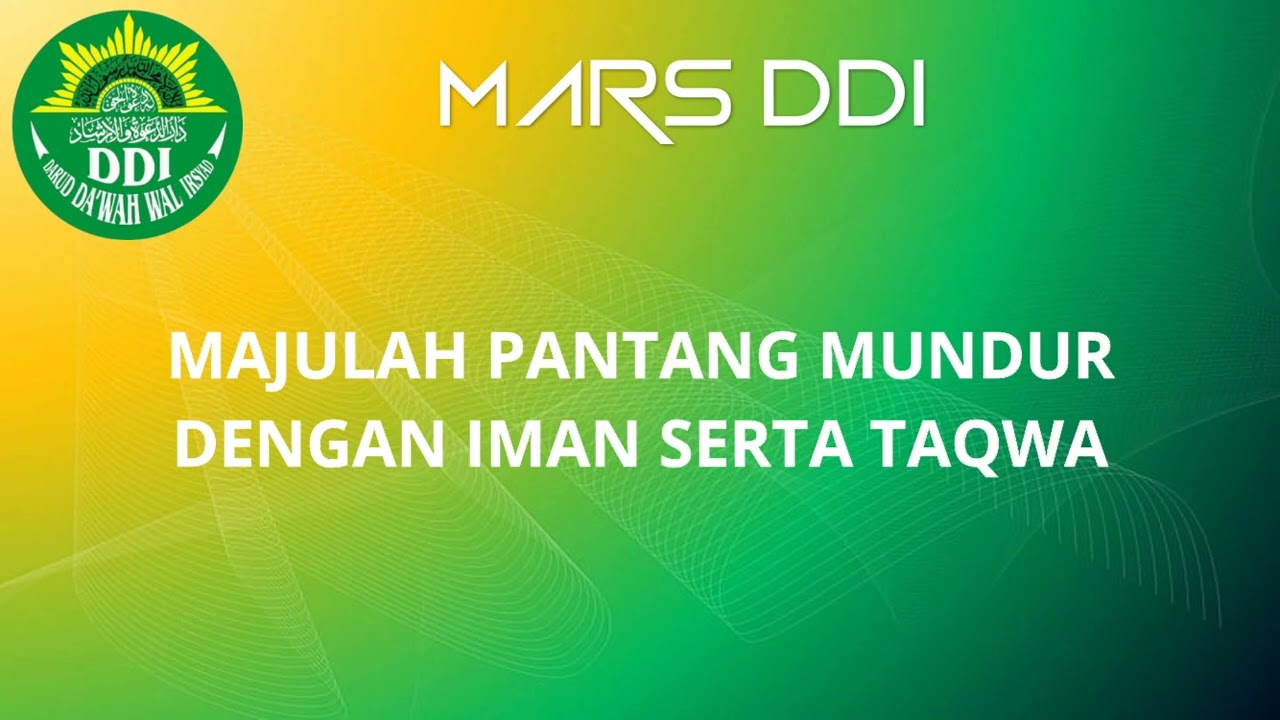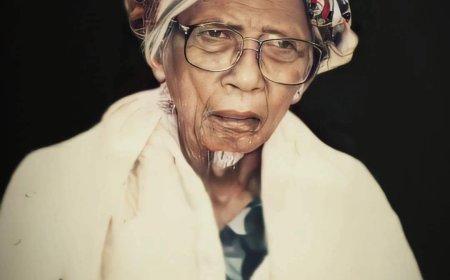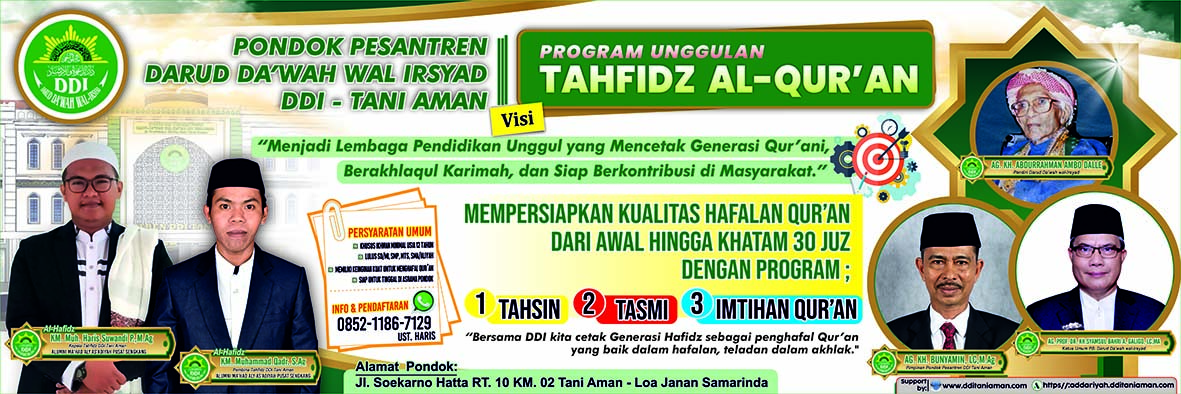Ekoteologi dalam Puisi Indonesia: Renungan dan Peringatan

Setiap kali hujan mengguyur deras hingga sungai meluap, setiap kali asap kebakaran hutan menutup langit, atau setiap kali kota kita diselimuti polusi yang menusuk paru-paru, kita seakan diingatkan bahwa alam sedang berbicara. Ia tidak sekadar menjadi latar kehidupan, melainkan subjek yang menuntut keadilan. Alam sedang bersuara, tetapi manusia sering kali tuli. Dalam kerangka inilah sastra, khususnya puisi memiliki posisi penting. Ia hadir bukan semata-mata untuk menghibur atau mendokumentasikan perasaan, melainkan untuk menyuarakan renungan sekaligus peringatan tentang bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan bumi.
Mengapa Puisi?
Pertanyaan pun muncul: mengapa kita perlu mendekati problem ekologis melalui puisi? Bukankah persoalan lingkungan lebih tepat dijawab dengan data ilmiah dan laporan teknis? Memang benar, sains memberi gambaran objektif tentang kerusakan alam. Data bisa menginformasikan bahwa Jakarta pernah menempati posisi pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Namun angka itu sering berhenti di layar gawai kita tanpa membekas di hati. Hanya bahasa sastra yang mampu membuat kita merasakan betapa sesak napas anak-anak yang tumbuh di kota itu.
Sains menyalakan alarm, tetapi puisi mengajak kita menyelami luka. Sains memberi tahu apa yang rusak, puisi menyadarkan mengapa kerusakan itu menyakitkan. Inilah alasan mengapa persoalan ekologis perlu dibaca melalui bahasa puisi: karena kerusakan lingkungan bukan hanya masalah teknis, melainkan juga tragedi kemanusiaan.
Dari Ekokritik ke Ekoteologi
Di sinilah gagasan ekoteologi menemukan relevansinya. Ekoteologi menegaskan bahwa relasi manusia dengan alam bukan semata relasi teknis atau ekonomis, melainkan relasi spiritual. Dalam tradisi agama-agama, bumi dipandang sebagai amanah, titipan yang harus dijaga. Merusak alam berarti mengkhianati kepercayaan Sang Pencipta. Dengan demikian, krisis ekologis bukan hanya kegagalan teknis, melainkan juga kegagalan moral.
Puisi yang menyingkap kesakralan alam dapat menjadi jembatan antara sains yang dingin dan agama yang penuh nilai. Puisi bekerja sebagai renungan batin, menghadirkan kesadaran bahwa gunung, laut, dan hujan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan ayat-ayat kehidupan yang harus dibaca dengan hormat.
Puisi sebagai Doa Ekologis
Sejak awal, penyair Indonesia sudah menunjukkan keakraban dengan alam. Muhammad Yamin dalam “Tanah Air” menulis:
Di atas batasan Bukit Barisan
Memandang beta ke bawah memandang:
Tampaklah hutan rimba dan ngarai
Lagipun sawah, telaga nan permai:
Serta gerangan lihatlah pula
Langit yang hijau bertukar warna
Oleh pucuk daun kelapa;
Itulah tanah, tanah airku
Sumatera namanya tumpah darahku.
…..
[Muhammad Yamin, “Tanah Air” (1922), dalam Parada Harahap (ed.), Puisi Indonesia Lama dan Baru, Jakarta: Balai Pustaka, 1977:42].
Baris ini menegaskan hidup-matinya hubungan spiritual antara penyair dan tanah kelahiran. Sumatra bukan sekadar ruang geografis, melainkan bagian dari jiwa, tubuh, dan identitas.
Demikian pula Ramadhan K.H. dalam Priangan Si Jelita melukiskan tanah Sunda dengan baris:
…..
Hijau tanahku,
hijau Tago,
dijaga gunung-gunung berombak.
Dan mawar merah
disobek di tujuh arah,
dikira orang menyanyi,
lewat di kayu kecapi.
…..
(Ramadhan K.H., Priangan Si Jelita (5), Jakarta: Pustaka Jaya, Cet.II, 1965).
Alam tampil bukan sekadar panorama, melainkan sosok jelita yang patut dikagumi sekaligus dilindungi.
Amir Hamzah pun, dalam doa-doa puitisnya seperti “Doa”, menyingkap keterhubungan manusia dengan Yang Mahasuci. Puisinya memperlihatkan bahwa angin, langit, dan laut bukan hanya ciptaan, tetapi juga rekan dialog spiritual:
Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku?
Dengan senja samar sepoi, pada masa purnama meningkat naik,
setelah menghalaukan panas terik.
…..
Amir Hamzah, “Padamu Jua”, Buah Rindu (Jakarta: Balai Pustaka, 1941).
Contoh-contoh ini membuktikan bahwa jauh sebelum istilah “ekokritik” atau “ekoteologi” populer, penyair Indonesia telah menyingkap dimensi ekologis dalam sajak mereka. Puisi telah menjadi doa ekologis, lahir dari kesadaran intuitif bahwa manusia tak bisa hidup terpisah dari alam.
Dari Estetika ke Etika
Puisi tentang alam bukan semata lukisan keindahan. Ia selalu berpotensi bergerak dari estetika menuju etika. Keindahan yang dihadirkan bukan untuk dipuja dari kejauhan, melainkan untuk disadari sebagai sesuatu yang mesti dijaga.
Ketika para penyair Maluku menerbitkan antologi Tana Putus Pusa (De La Macca, 2019), mereka tidak sekadar menuliskan panorama Banda atau suara hujan, melainkan juga kegelisahan ekologis. Judul-judul seperti “Negeri Damai”, “Perempuan di Tepi Laut Banda”, atau “Betapapun Hujan adalah Namamu” memuat kerinduan sekaligus peringatan. Laut bukan hanya sumber ekonomi, melainkan ruang spiritual yang rapuh. Jika laut rusak, maka bukan hanya ekosistem yang hancur, melainkan juga identitas dan spiritualitas masyarakat.
Dengan demikian, puisi ekologis mengajarkan: mencintai alam berarti mencintai diri sendiri. Kerusakan ekologis adalah kerusakan kemanusiaan.
“Pemandangan”: Ekologi sebagai Renungan Eksistensial
Puisi karya D. Zawawi Imron ini menampilkan lanskap ekologis yang sarat dengan muatan batin:
Pemandangan
Kubiarkan bakau-bakau di rawa pantai itu melanjutkan pesanmu, awan jingga, langit jingga, angin jingga dan laut jingga
Riak air yang belas padaku menghiba sepanjang lagu, dahan-dahan yang sudah mati kembali menari-nari menyambut embunmu senjahari
Di tengah laut namamu bermain cahaya, aku sangat ingin ke sana, tapi terasa dengan sampan seribu tahun aku tak sampai
Dengan keharuan, mungkinkah cukup satu denyutan?
1978
(dalam buku puisi, Bulan Tertusuk Lalang, Balai Pustaka, 1982)
Lanskap senja, “awan jingga, langit jingga, angin jingga, dan laut jingga”, menggambarkan harmoni kosmos yang mengikat warna, cahaya, dan jiwa. Namun, puisi ini juga menyiratkan keterbatasan manusia: “Di tengah laut namamu bermain cahaya, aku sangat ingin ke sana, tapi terasa dengan sampan seribu tahun aku tak sampai.”
Laut di sini adalah simbol ruang ekologis yang agung, tetapi juga menyingkap jurang eksistensial antara manusia dan semesta. Puncaknya, pertanyaan lirih penyair, “Dengan keharuan, mungkinkah cukup satu denyutan?” menjadi refleksi universal: kehidupan manusia terlalu singkat untuk menjelajahi seluruh rahasia alam.
“Pemandangan” puisi D. Zawawi Imron ini, memperlihatkan bahwa menjaga alam sama artinya dengan menjaga diri sendiri. Kesadaran ekologis ini bersifat eksistensial sekaligus spiritual.
Alam sebagai Ayat
Mengapa puisi memiliki kekuatan untuk mengaitkan alam dengan dimensi spiritual? Karena bahasa puisi dekat dengan bahasa doa.
Dalam ekoteologi, alam dipandang sebagai ayat, bukan ayat kitab suci yang tertulis, melainkan ayat semesta yang terbentang. Gunung, hujan, laut, dan angin dapat dibaca sebagai pesan tentang keteraturan kosmos, kebesaran pencipta, sekaligus kerentanan hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh John Hart dalam bukunya What Are They Saying About Environmental Theology? (New York: Paulist Press, 2004:15-18), ekoteologi menekankan bahwa seluruh ciptaan adalah teks teologis yang menyampaikan pesan ilahi. Dengan demikian, membaca puisi ekologis menyerupai membaca doa: ia mengajak kita merenung, mengakui keterbatasan, sekaligus berjanji untuk menjaga.
Akar ekoteologi dalam puisi Indonesia sangat kuat. Banyak penyair lahir dari kultur religius yang memandang keterhubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai kesatuan. Itulah mengapa puisi ekologis kita jarang berhenti pada deskripsi indah; ia hampir selalu bermuara pada perenungan etis.
Contoh paling kuat hadir dalam puisi karya Sapardi Djoko Damono ini:
Hujan Bulan Juni
tak ada yang lebih tabah
dari hujan bulan Juni
dirahasiakannya rintik rindunya
kepada pohon berbunga itu
tak ada yang lebih bijak
dari hujan bulan Juni
dihapusnya jejak-jejak kakinya
yang ragu-ragu di jalan itu
tak ada yang lebih arif
dari hujan bulan Juni
dibiarkannya yang tak terucapkan
diserap akar pohon bunga itu
1989
(dalam buku puisi, Hujan Bulan Juni, Gramedia, 1994)
Hujan, yang biasanya dianggap sekadar fenomena alam, diubah Sapardi menjadi simbol kesabaran yang spiritual. Baitnya yang terkenal, “tak ada yang lebih tabah / dari hujan di bulan Juni”, memperlihatkan bagaimana alam berbicara dengan bahasa ketabahan. Hujan tidak hanya hadir sebagai air yang jatuh, tetapi sebagai “ayat semesta” yang mengajarkan manusia tentang ketekunan, penerimaan, dan kerelaan. Seperti doa yang lirih, puisi ini memandang alam bukan dari fungsinya yang material, melainkan dari pesan etis dan spiritual yang dibawanya. Dengan demikian, Sapardi berhasil menunjukkan bahwa hujan dapat menjadi wahyu kecil yang memberi manusia hikmah tentang sabar dan ikhlas.
Sementara itu, D. Zawawi Imron dalam puisinya “Sungai Kecil” menggarisbawahi dimensi batiniah dari alam. Baginya, sungai bukan sekadar aliran air, melainkan arus spiritual yang menembus jantung kehidupan:
…..
Sungai kecil, sungai kecil! Mengalirlah terus ke rongga jantungku
dan kalau kau payah, istirahatlah ke dalam tidurku! Kau yang
jelita kutembangkan buat kekasihku.
Sungai di sini tampil sebagai lambang doa yang mengalir tanpa henti, menyucikan batin, dan menyambungkan manusia dengan Sang Sumber Kehidupan. Dalam kerangka ekoteologi, sungai adalah ayat tentang kontinuitas rahmat Ilahi dan pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari aliran besar kosmos. Zawawi menghidupkan tradisi sufistik yang melihat alam sebagai cermin ketuhanan, setiap aliran sungai adalah tasbih yang mengalun kepada Sang Khalik.
Jika Sapardi menempatkan hujan sebagai ayat kesabaran, maka Zawawi menghadirkan sungai sebagai ayat doa. Dua pendekatan ini menunjukkan keluasan tradisi puisi Indonesia dalam menafsirkan alam sebagai teks spiritual, baik melalui liris modern yang kontemplatif maupun melalui religiositas sufistik yang mengakar.
Dengan membaca kedua puisi tersebut, jelas bahwa alam dalam puisi Indonesia bukanlah lanskap pasif, melainkan teks spiritual yang harus “dibaca”. Alam menjadi doa yang bergetar, ayat yang mengalir, sekaligus amanah etis bagi manusia.
Dari Renungan ke Tindakan
Tentu muncul pertanyaan: apakah puisi cukup untuk menghentikan pembalakan liar atau mencegah korporasi tambang merusak hutan? Jelas tidak. Puisi tidak bisa menggantikan kebijakan publik atau teknologi ramah lingkungan.
Namun, puisi punya peran yang tak tergantikan: membangun kesadaran. Tanpa kesadaran, kebijakan apa pun akan gagal. Tanpa kesadaran, teknologi paling canggih pun hanya akan dipakai untuk mengeksploitasi lebih banyak. Dengan kata lain, puisi bukan akhir, melainkan awal. Ia adalah panggilan batin yang membuat manusia berhenti sejenak dari kesibukan eksploitatif untuk bertanya: apa yang telah kita lakukan pada bumi?
Kesusastraan sebagai Alarm Kemanusiaan
Sejarah membuktikan bahwa sastra sering berfungsi sebagai alarm moral. Novel menggugah kesadaran kelas, cerpen membuka mata terhadap ketidakadilan gender, dan puisi menyuarakan protes terhadap perang (Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction, Oxford: Blackwell, 1996:202-205). Dalam konteks ekologis, puisi berfungsi sebagai alarm kemanusiaan.
Alarm itu hadir bukan melalui teriakan, melainkan kelembutan: citraan tentang hutan yang meranggas, laut yang kehilangan ikan, atau anak kecil yang batuk karena asap kebakaran. Justru kelembutan itulah yang menyentuh. Jika sains berbicara dengan angka, puisi berbicara dengan rasa. Dan keduanya hanya efektif jika berjalan beriringan.
Peringatan yang Lembut
Kita hidup di zaman ketika bumi semakin lelah. Krisis iklim bukan lagi wacana jauh, melainkan realitas sehari-hari. Dalam situasi ini, kita memerlukan peringatan yang tak hanya bersuara keras lewat sirene, tetapi juga peringatan lembut yang meresap ke hati. Puisi menawarkan itu.
Ekoteologi dalam puisi Indonesia menunjukkan bahwa menjaga bumi bukan semata kewajiban ekologis, melainkan juga panggilan spiritual. Puisi mengingatkan bahwa bumi adalah rumah bersama, sekaligus kitab terbuka yang harus dibaca dengan hormat.
Ketika penyair menulis tentang sungai yang keruh atau laut yang tercemar, itu bukan sekadar metafora; itu doa yang menunggu jawaban dari tindakan kita. Membaca puisi ekologis berarti menerima renungan sekaligus ajakan.
Pada akhirnya, puisi ekologis adalah renungan dan peringatan. Renungan agar kita menyadari keterhubungan dengan alam; peringatan agar kita tidak terus-menerus mengkhianati bumi. Barangkali, dalam keheningan membaca puisi itu, kita menemukan kembali suara bumi yang lama kita abaikan: suara yang sekaligus adalah gema hati kita sendiri. ***
Abdul Wachid B.S. (Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Purwokerto)
Apa Reaksi Anda?
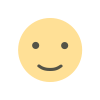 Suka
0
Suka
0
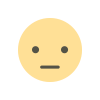 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
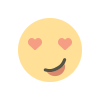 Cinta
0
Cinta
0
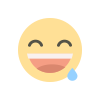 Lucu
0
Lucu
0
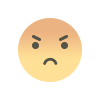 Marah
0
Marah
0
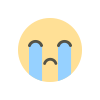 Sedih
0
Sedih
0
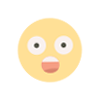 Wow
0
Wow
0